
Langit Kurukshetra mendung sejak fajar. Awan-awan hitam menggantung seperti jaring-jaring para dewa yang menanti untuk menjatuhkan hukuman. Seekor bangau putih melintas rendah, lalu menghilang ke balik kabut tebal. Tak jauh dari situ, seekor buaya tampak muncul di permukaan sungai Saraswati, diam dan mengintai. Kedua pertanda itu tak luput dari pandangan para brahmana tua. Mereka berbisik pada diri sendiri—bahwa pertempuran hari ini akan menjadi pertarungan antara kelicikan dan kekuatan murni.
Di satu sisi, Kurawa membentangkan formasi Kraunchabyuha, seperti bangau raksasa yang hendak mencabik. Di sisi lain, Pandawa menyusun Makarabyuha, formasi buaya yang menanti dengan rahang terbuka.
Bima berdiri di atas keretanya. Nafasnya memburu. Matanya menatap satu titik: Resi Durna.
Pertarungan pun dimulai.
Seperti petir jatuh dari langit, Bima menerjang ke arah gurunya itu dengan kekuatan luar biasa. Gada Rujakpala menghantam keras, menciptakan guncangan di tanah Kurukshetra. Tapi Resi Durna, meski telah tua, bergerak dengan kecepatan ular. Ia menangkis, memutar pedang, dan menyerang dengan ketepatan mengerikan. Bima meraung, Durna tetap hening. Pertarungan itu seperti gunung api melawan samudra dalam.
Namun Resi Durna tak datang untuk sekadar bertarung. Dengan isyarat cepat, ia memacu kereta kudanya, menembus celah dalam formasi Pandawa. Dalam sekejap, ia telah berada di jantung pasukan Pancala, melepaskan panah-panah mematikan yang bagaikan badai tak kasatmata. Barisan Pandawa tercerai-berai, kuda terjungkal, panah membakar kereta, dan tanah menjadi merah oleh darah.
Dari kejauhan, Arya Drestajumena menyaksikan kehancuran itu. Wajahnya membeku. Tanpa ragu, ia mencabut tombaknya dan mengangkat tinggi ke langit, lalu berseru lantang, “Wahai Resi, jangan lagi kau sembunyikan tanganmu di balik jubah guru!” Keretanya melesat, menerobos debu dan kobaran, menuju pusat badai yang diciptakan sang resi.
Di sisi lain medan, Bima tak tinggal diam. Ia telah menembus garis pertahanan Kurawa, namun dalam waktu singkat ia dikepung dari segala penjuru. Pasukan Kurawa datang dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Panah dilepaskan, tombak dilemparkan. Namun Bima, sang putra Bayu, tak memilih mundur.
Dengan raungan membelah langit, ia melompat dari keretanya. Tanah bergetar saat tubuh raksasanya menghantam bumi. Debu mengepul. Suara gada Rujakpala berputar laksana badai memekakkan telinga. Satu hentakan menghancurkan lima prajurit, satu ayunan memecahkan perisai, menembus daging dan tulang. Musuh-musuhnya lari terbirit, tapi tak semua sempat selamat. Bima mengamuk di tengah kepungan seperti dewa maut turun dari langit.
Namun jumlah tetaplah jumlah. Tubuh Bima mulai berdarah, bahunya tertusuk, dan kakinya tergores. Meski semangatnya membara, dagingnya tetaplah fana.
Lalu kabut terbuka.
Derap roda kereta terdengar mendekat, tajam dan pasti. Arya Drestajumena datang lebih dulu, tombaknya menyambar seperti kilat di antara pasukan Kurawa, membuka jalan bagi sang pahlawan. Tak lama, kereta kedua meluncur seperti panah dilepaskan dari busur ilahi. Di atasnya berdiri seorang pemuda gagah, wajahnya menyala dan matanya membara—Abimanyu, putra Arjuna.
Keduanya bergabung di sisi Bima. Tak ada kata. Tak perlu.
Bima menoleh sekilas, tersenyum pendek. “Mari kita pecahkan bumi ini.”
Dan mereka pun membentuk poros maut di tengah medan: Bima menggulung dari tengah, Drestajumena menusuk dari sisi kiri, Abimanyu memanah dari atas keretanya, cepat dan kejam. Pasukan Kurawa terombang-ambing, kehilangan arah, kehilangan pemimpin. Di tengah teriakan dan dentang senjata, tiga ksatria Pandawa menari dalam kematian, seperti roda tak terhentikan yang menggiling apa pun yang menghalangi.
Sementara itu, Prabu Duryudana yang melihat kehancuran pasukannya maju menghadapi Drestajumena. Dua musuh lama kembali bertemu, dan duel keduanya menciptakan lingkaran baru di tengah kekacauan.
Namun langit mulai berubah. Sinar jingga muncul di barat. Matahari perlahan turun, memandikan medan dengan cahaya keemasan yang ganjil—indah dan menyayat hati.
Dan justru di saat itulah, Resi Bisma Dewabrata, tua namun masih berdiri seperti gunung, mulai mengamuk.
Ia tak mengincar ksatria. Ia menghantam prajurit, menghancurkan barisan belakang, merobohkan kuda dan kereta. Ia bertempur dengan kesunyian dalam dadanya. Sumpahnya untuk membela Hastinapura membakar tubuh renta itu. Tapi jauh di balik kekuatan dan ketekunannya, ada kesedihan yang tak terucap—karena ia tahu, perang ini tak bisa dimenangkan, hanya bisa ditamatkan.
Ia menatap langit yang mulai temaram. Tapi tangannya belum berhenti. Tidak sampai malam datang. Tidak sebelum panggilan senyap itu datang dari dalam hatinya sendiri.
Akhirnya, sangkakala ditiup. Genderang ditabuh tiga kali. Matahari tenggelam di barat, merah dan basah seperti luka yang belum sembuh. Pasukan dari kedua sisi mulai mundur, tubuh-tubuh dikumpulkan, tangis dan raung memenuhi tenda-tenda.
Hari keenam pun berakhir.
Namun medan masih merah. Dan dendam masih menetes bersama darah di tanah Kurukshetra.
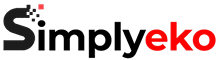
Leave a Reply