
Kabut tipis menggantung rendah di atas padang Kurukshetra. Matahari pagi menyembul lambat dari balik horison, namun cahayanya tampak redup, seolah enggan menyinari ladang kematian itu. Pasukan dari kedua belah pihak tak lagi segagah hari-hari pertama. Mata cekung, langkah berat, dan sorot penuh lelah kini menghantui wajah-wajah para prajurit. Namun gendang perang kembali ditabuh.
Kurawa membentang Kurmawyuha, formasi tempur seperti tempurung kura-kura—bertahan dan memukul dengan keras dari balik perlindungan. Pandawa menyusun Trisulabyuha, tiga tombak menusuk tajam ke jantung pertahanan musuh. Tidak ada waktu untuk ragu. Tidak ada ruang untuk jeda.
Dan di tengah semua itu, Bima berjalan perlahan menuju medan utama, seperti badai yang menjemput sasarannya. Tubuhnya dibalut darah dari tujuh hari sebelumnya. Gada Rujakpala berada di tangan, dan matanya menyala, bukan karena amarah semata, tapi karena tugas yang belum selesai.
Ia menghadapi Kurawa satu per satu.
Arya Dursasana menyerang lebih dulu—Bima memutar gada dan menghancurkan perisainya, lalu merobohkannya dengan satu hantaman yang mengguncang tanah. Arya Durpramata menyergap dari belakang, namun Bima membanting tubuhnya seperti karung gandum yang basi. Dan begitu seterusnya: Durprasadarsa, Dursaha, Dursaya… semuanya bertumbangan satu demi satu, bukan dengan kebencian, tapi dengan keteguhan seorang ksatria yang tahu: ini bukan pembalasan pribadi, ini penghabisan bagi kezaliman.
Tubuh-tubuh mereka bergelimpangan, membentuk semacam jalur merah menuju takhta Kurawa.
Dari kejauhan, Prabu Duryudana menyaksikan. Wajahnya menegang, hatinya mendidih. Ia berteriak: “Majulah! Habisi Bima! Dia sendiri! Kau, Arya Durkusuma! Kau, Durwikata! Bunuh dia!”
Tak satu pun bergerak.
Mereka menunduk. Beberapa melangkah mundur. Yang lain hanya memandangi tubuh-tubuh saudaranya dengan wajah pucat. Sosok Bima terlalu besar, terlalu penuh bayang-bayang kematian.
“Pengecut semua!” Duryudana menggeram, suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bukan hanya kemarahan, tetapi kehilangan. Kekuasaan tanpa pengikut. Saudara tanpa nyali. Dan bayangan Bima semakin lama semakin memakan tahtanya.
Sementara itu, di medan berbeda, Resi Durna berhadapan dengan Gatotkaca.
Anak dari Bima dan raksasa Perwati itu terbang seperti petir, memutar kereta musuh, menjatuhkan batu dari langit, dan mengguncang barisan Kurawa. Tapi Durna tidak membalas dengan kekuatan—ia menjawab dengan akal. Ia mengatur siasat, menebar mantra, dan membaca celah dari gerak Gatotkaca. Mereka seperti api dan air, muda dan tua, ganas dan tenang. Namun pertempuran tak menghasilkan pemenang hari itu, hanya luka dan kekaguman yang saling tertanam dalam hati masing-masing.
Menjelang siang, suara derap kuda menggema keras dari utara medan. Barisan berkuda Pandawa datang menerjang—dan di garis terdepan berdiri seorang pemuda yang belum pernah terlihat sebelumnya: Bambang Irawan, putra Arjuna dari Dewi Ulupi.
Jubah hijau zamrudnya berkibar ditiup angin. Panahnya bersinar keperakan, dan wajahnya memancarkan semangat muda yang belum disentuh racun kebencian perang. Ia memimpin dengan tenang namun teguh, menembus serangan demi serangan Arya Sangkuni dan pasukannya yang terus mengancam sayap Pandawa.
Sorakan bergema dari belakang. Ksatria muda itu bagaikan cahaya baru di tengah ladang yang sudah lama dibalut gelap.
Melihat pamannya kewalahan, Prabu Duryudana menggeretakkan giginya, lalu berkata pada seorang pengawalnya: “Panggilkan Ditya Srenggi. Hari ini, cahaya baru itu harus padam.”
Tak lama kemudian, dari balik pasukan Kurawa, muncul sesosok tinggi besar dengan wajah kelam dan senjata bermata dua di punggungnya. Ditya Srenggi. Tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk saat tahu siapa lawannya.
Pertemuan mereka terjadi di tengah ladang sunyi. Pasukan lain seolah menahan napas. Dua ksatria muda, dua takdir yang bersilangan, dua kekuatan yang dipertemukan oleh nasib.
Bambang Irawan dan Ditya Srenggi saling menatap. Lalu saling memberi hormat.
“Semoga kita bertempur dalam hormat,” ujar Irawan.
“Dan gugur tanpa dendam,” jawab Srenggi.
Pertarungan meledak. Pedang beradu, panah melesat, tombak menebas. Kuda roboh, senjata terpental, tubuh berdarah. Tapi tak ada kebencian—hanya tekad. Tubuh mereka luka. Napas mereka tersengal. Namun tak satu pun mundur. Sampai akhirnya, dalam satu gerakan saling tusuk—panah Irawan menembus dada Srenggi, dan tombak Srenggi menghujam perut Irawan.
Mereka saling memandang. Mata mereka bersinar damai.
Lalu perlahan, mereka rebah, bersandar satu sama lain. Nyawa meninggalkan tubuh dalam tenang, bukan dalam jerit.
Saat malam mulai turun, dan terompet perang ditabuh tanda penarikan pasukan, tubuh dua ksatria muda itu masih bersandar, seakan tidur dalam keheningan yang suci.
Bagi Pandawa dan Kurawa, hari kedelapan adalah hari darah, air mata, dan cahaya yang padam. Tapi bagi langit, ini adalah hari ketika dua jiwa mulia kembali pulang… bersamaan.
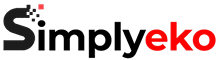
Leave a Reply