
Pagi turun di Kurukshetra tanpa cahaya terang. Matahari yang biasanya muncul sebagai janji, hari ini tenggelam di balik awan kelabu. Angin kencang membawa debu dan daun kering, mengitari tenda-tenda para ksatria yang hanya menatap diam ke arah medan perang. Tak satu pun berkata-kata, namun dada mereka tahu: hari ini, sesuatu yang besar akan terjadi.
Pasukan Pandawa menyusun Garudawyuha—formasi seperti burung garuda yang hendak mencabik. Di sisi berlawanan, Kurawa membentuk Ardhachandrabyuha, melengkung seperti bulan sabit, siap memotong sayap garuda itu dari tengah.
Dan dari sayap kanan Pandawa, muncul seorang ksatria muda, gagah, berani, dan tak menyisakan keraguan: Abimanyu, putra Arjuna.
Ia melesat ke depan dengan derap kudanya yang keras, busur di tangan, mata tajam menatap ke dalam jantung pasukan Kurawa. Tak ada waktu untuk basa-basi. Tak ada jeda untuk ragu. Ia menerobos garis musuh seperti kilat yang menusuk malam. Panah-panahnya melesat cepat, memecah barisan, mematahkan perisai, menjatuhkan kereta. Ia menari di tengah peperangan, bukan dengan murka, melainkan dengan takdir.
“Dia Arjuna muda,” bisik prajurit Kurawa ketakutan. “Atau mungkin… lebih dari itu.”
Tak seorang pun ksatria Kurawa sanggup menahannya. Satu per satu tumbang, sebagian lari, sebagian menyerah. Maka muncullah sosok agung di kejauhan, berdiri di atas kereta putihnya dengan jubah seperti kabut senja: Resi Bisma Dewabrata.
Abimanyu menahan kudanya. Mereka saling menatap. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam.
“Maafkan aku, Eyang,” kata Abimanyu lirih. “Hari ini aku berdiri di jalan dharma.”
Bisma mengangguk. “Dan aku masih terikat pada sumpah.”
Lalu mereka bertarung. Tidak seperti dua musuh, tapi seperti gunung dan badai—keduanya saling mencoba menjatuhkan namun tahu, hanya waktu yang bisa memilih siapa yang akan runtuh lebih dulu. Panah demi panah, langkah demi langkah, setiap benturan mereka adalah simfoni takdir yang menari di udara.
Dari sisi timur, Arjuna melihat putranya dikepung. Ia menderap cepat, namun langkahnya terhenti.
Di hadapannya berdiri Resi Durna, gurunya sendiri.
“Arjuna,” ucap Durna dengan suara pelan, “kau datang untuk menyelamatkan anakmu, tapi jalan itu kulindungi.”
Arjuna menarik napas panjang. “Guru… aku tak ingin melukaimu.”
“Tapi panahmu tetap akan menuju padaku.”
Dan mereka pun bertarung—dengan air mata dan amarah. Setiap tebasan Arjuna menyimpan ragu. Setiap serangan Durna menyimpan kasih. Tapi di medan perang, cinta tak punya tempat. Yang tersisa hanya siasat, kekuatan, dan tangisan diam yang tertahan di dada.
Melihat Arjuna nyaris terdesak, Arya Setyaki menerjang dari arah barat, hujan panahnya membelah langit. “Aku tak akan biarkan sahabatku jatuh tanpa saudara di sisinya!”
Namun dari kejauhan datang juga Bambang Aswatama, putra Durna. Matanya redup, wajahnya tenang, namun busurnya penuh amarah.
“Kau bukan siapa-siapa bagiku, Setyaki. Tapi ayahku kau ganggu. Itu cukup jadi alasanku.”
Dua pemuda—dua pewaris generasi maha ksatria—bentrok. Bukan hanya tenaga mereka yang saling menguji, tapi juga harga diri, warisan, dan keyakinan. Ledakan demi ledakan senjata memekakkan udara. Mereka saling memburu dan menghindar, menantang dan menggugat.
Di pusat pertempuran, Abimanyu mulai lelah. Dan Arjuna—meski telah membebaskan dirinya dari Durna—masih belum mampu menghadapi kenyataan di hadapannya.
Sebab yang kini berdiri di hadapannya adalah kakeknya sendiri, Resi Bisma.
Ia kembali gemetar.
Panahnya melesat, tapi tak mengarah ke titik maut. Jarinya kaku. Dadanya sesak.
Melihat itu, dari kejauhan, Prabu Sri Kresna yang diam selama ini akhirnya melangkah maju.
Langit berubah. Angin berhenti. Seolah semesta pun tahu: titisan Wisnu sedang bangkit.
Langkah demi langkah ia ambil ke tengah medan, dan ketika ia mengangkat tangannya, cakra sudarsana muncul dari cahaya, berputar di udara bagaikan bintang menyala. Terang dan panas.
“Arjuna!” teriaknya. “Sampai kapan kau biarkan kebenaran tertahan oleh rasa hormat? Dharma tidak bisa disandera oleh nostalgia!”
Arjuna menggigil. “Dia… kakekku…”
“Dan dia berdiri di sisi adharma!” teriak Kresna. “Jika kau tak mampu, aku yang akan mengakhirinya!”
Langkah Kresna bergetar di tanah. Cakra mendekat ke arah Resi Bisma. Suara pasukan terdiam. Dunia menahan napas.
Namun Bisma tidak bergerak. Ia hanya menatap cakra itu, lalu menutup mata perlahan.
“Jika ini akhirku, biarlah datang dari tangan titisan Wisnu. Tak ada kematian yang lebih mulia.”
Cakra makin dekat.
Arjuna berteriak: “Kresna! Jangan!”
Ia berlari dan meraih tangan Kresna. Yudistira dan Bima ikut menahan. Cakra berhenti. Menggantung. Lalu lenyap perlahan dalam kilatan lembut.
Kresna menatap Arjuna, matanya masih membara. “Hari ini kau menunda takdir. Tapi esok… kau tak boleh gagal lagi.”
Dan langit perlahan mendung kembali.
Di kejauhan, Abimanyu kembali berdiri. Luka-lukanya banyak. Tapi matanya tetap tajam.
Ia tak tahu, di hari-hari berikutnya, kematiannya akan menjadi pintu menuju kehancuran Kurawa.
Tapi hari itu, ia hidup—dan seluruh medan perang tahu: meski Arjuna ragu, anaknya tidak.
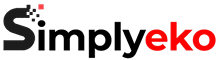
Leave a Reply