
Langit Kurukshetra hari itu menggantung kelabu, seolah para dewa enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin bertiup ganjil, membawa bau darah yang belum kering dari hari-hari sebelumnya. Di kejauhan, burung-burung pemakan bangkai beterbangan rendah, mengitari medan perang bahkan sebelum genderang pertama ditabuh. Ada firasat yang membungkam dada—seakan bumi sendiri menggigil dalam diam.
Di sisi Pandawa, tak seorang pun banyak berkata pagi itu. Prabu Yudistira hanya menatap cakrawala dengan mata nanar. Sementara itu, Abimanyu—masih muda, masih penuh semangat—mengecup tangan ayahandanya Arjuna, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi penutup usianya yang belum sempat mekar sepenuhnya.
Ketika formasi Cakrawyuha Kurawa mulai menggulung ke tengah medan, hanya satu suara yang melangkah maju dari barisan Pandawa: Abimanyu. Ia tahu rahasia memasuki formasi itu, sebagaimana pernah didengar dari ayahandanya. Tapi ia tak tahu cara keluar darinya—dan ia tetap memilih untuk maju.
Arjuna tak berada di sisi itu, karena sedang ditahan jauh di medan lain oleh siasat licik Jayadrata. Maka hanya Sri Kresna yang melihat langkah sang keponakan, dan menatapnya dengan mata yang menyimpan ribuan kemungkinan. “Ia seperti seekor burung yang terbang ke dalam badai,” ujar Kresna lirih, kepada udara yang tak menjawab.
Yudistira sempat melarang, namun Abimanyu tersenyum—bukan senyum sombong, melainkan senyum orang yang sudah berdamai dengan nasibnya.
“Aku putra Arjuna,” katanya, “dan hari ini, biarlah dunia mengingatku bukan karena nama ayahku… tapi karena keberanianku.”
Para Pandawa hanya bisa menyaksikan, saat Abimanyu menunggang keretanya menembus lingkaran Cakrawyuha seperti cahaya menembus awan gelap—tanpa tahu bahwa tak akan ada jalan pulang.
Ia menebas kiri dan kanan, menghunus panah secepat kilat, menjatuhkan lawan satu demi satu. Bambang Lesmana Mandrakumara, putra mahkota Hastina, mencoba menghadapinya—dan dalam satu sabetan cepat, Abimanyu menebas takhta masa depan Hastina menjadi dua. Tubuh Lesmana roboh tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun.
Namun kemenangan itu hanya sesaat.
Dari kejauhan, Adipati Karna menyiapkan busurnya. Ia tahu Abimanyu tak menyadarinya. Dan dengan hati yang dingin, ia melepaskan panah ke punggung Abimanyu, menghancurkan busurnya dari belakang—langkah pertama pengkhianatan terhadap dharmayudha.
Kereta Abimanyu ditabrak dan dihancurkan oleh Aswatama, yang melepaskan dua panah sekaligus ke bagian bawah kereta. Kuda-kudanya tewas. Kusirnya terlempar. Burisrawa datang dan menebas tali kekang yang tersisa, lalu menyerang senjata-senjata cadangan Abimanyu dan menjatuhkannya satu per satu. Pedangnya sempat terhunus—namun patah di tangan.
Kini Abimanyu berdiri di tengah kerumunan musuh tanpa kereta, tanpa kuda, tanpa senjata. Ia menarik napas. Menatap sekeliling. Matanya tak gentar, tapi jelas—ia tahu, ia sedang dikhianati oleh dunia yang menyebut dirinya ksatria.
“Beginikah caramu mengalahkanku?” katanya pelan. “Bukan dengan keberanian, tapi dengan jumlah? Kalian takut pada seorang remaja yang sendirian?”
Tak satu pun menjawab.
Ia meraih roda keretanya yang rusak dan mengangkatnya seperti perisai. Dengan itu ia menangkis panah demi panah, mengayun bagai dewa perang muda. Namun jumlah itu tak bisa ia lawan selamanya.
Ratusan panah menghujaninya.
Tubuhnya tertancap dari kaki hingga dada. Ia tersungkur. Dan saat tubuhnya tak lagi bergerak, Arya Jayadrata maju. Dengan wajah dingin dan mata tak berkedip, ia mencincang tubuh Abimanyu yang telah tak berdaya. Bahkan kematian pun tidak dibela oleh kehormatan hari itu.
Petang menjelang saat kabar itu tiba.
Seorang prajurit datang tergopoh membawa bendera kecil bersimbah darah. Arjuna menatapnya, dan tahu bahkan sebelum suara keluar dari mulut prajurit itu.
“Abimanyu…” bisiknya.
“Telah gugur, Prabu,” kata sang prajurit, suaranya tercekat. “Mereka… mereka mencincangnya setelah ia roboh.”
Dunia seakan runtuh. Arjuna terdiam. Tangannya mengepal, matanya membelalak, napasnya tercekat. Lalu ia berteriak, bukan seperti ksatria, tapi seperti ayah yang kehilangan darah dagingnya.
Ia menjatuhkan busurnya. Berlutut. Menggenggam debu Kurukshetra dan mencampurnya dengan air matanya sendiri.
“Mereka tak membunuhnya… mereka menghancurkannya!” serunya. “Dan aku… ayahnya… tak mampu menjaganya!”
Sri Kresna mendekat, tidak dengan kata-kata, hanya menatap sahabatnya itu dengan mata yang dalam. Tidak ada pelipur lara bagi duka semacam ini. Hanya keheningan dan langit yang ikut memerah, seolah ikut menangis.
Setelah lama diam, Arjuna berdiri perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah yang sama.
“Jika matahari esok tenggelam dan Jayadrata masih bernapas…” suaranya gemetar oleh dendam, “…maka aku akan menebas diriku sendiri dengan tanganku ini.”
Sri Kresna memejamkan mata dan mengangguk.
“Maka kita pastikan,” ujarnya pelan, “bahwa matahari tidak akan tenggelam sebelum Jayadrata gugur.”
Malam tiba di Kurukshetra bukan sebagai ketenangan, tapi sebagai selimut duka. Tak ada nyanyian kemenangan, tak ada sorak ksatria. Hanya angin yang menderu pelan, membawa aroma darah dan abu. Langit tak menampakkan bintang malam itu—seolah para dewa pun memalingkan wajah mereka dari bumi.
Pandawa berkemah dalam diam. Tak seorang pun bersuara. Drestajumena duduk bersila memandangi tanah, seperti membaca jejak-jejak kematian. Sadewa dan Nakula berjaga, tapi tanpa semangat. Yudistira hanya memandangi api unggun yang nyalanya lesu.
Di sudut tenda, Arjuna duduk sendiri, tangannya masih menggenggam panah tapi tubuhnya seolah tanpa jiwa. Wajahnya tak menangis, tapi hancur. Ia tak butuh kata-kata belasungkawa. Ia hanya butuh fajar datang membawa Jayadrata ke hadapannya.
Dan di luar sana, Sri Kresna berdiri memandangi langit. Jubahnya bergoyang perlahan diterpa angin malam. Ia tahu, keseimbangan dunia baru saja bergeser. Perang ini bukan lagi tentang tanah atau takhta—ini sudah menyentuh akar terdalam hati manusia. Dan ketika seorang ayah kehilangan anaknya, bumi pun akan terbakar oleh api pembalasan.
“Hari ini,” bisik Kresna kepada malam, “dharmayudha telah tercabik. Maka besok… dharma akan berbicara lewat panah.”
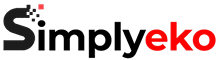
Leave a Reply