
Langit Kurukshetra bergolak, angin membentur debu yang menggantung. Di atas kereta yang kini tak bergerak, Prabu Sri Kresna berdiri tegak, kedua matanya menatap cakrawala—bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan kepastian seorang yang tahu batas waktu sudah cukup diberikan.
Tanpa berkata sepatah pun, Kresna mengangkat tangan kanannya. Cakra Beskara—senjata cahaya yang hanya patuh pada kehendaknya—mulai berputar pelan di udara, mengeluarkan bunyi seperti auman halilintar yang tertahan.
Langit mendadak suram. Seolah-olah dunia menarik napas terakhirnya. Matahari, sang saksi abadi, tertelan bayangan, seakan sebuah gerhana turun tanpa peringatan. Prajurit dari kedua belah pihak berhenti. Tak ada lagi yang meneriakkan perintah, tak ada panah yang dilepas. Semua diam—seperti bumi ditarik dalam kehampaan suci.
Kresna tidak menjelaskan. Ia tidak perlu menjelaskan. Ia hanya menoleh ke arah Arjuna, dan berkata tegas, datar, seperti suara takdir itu sendiri:
“Sekarang.”
Langit seolah menahan napas.
Dari balik bayang-bayang, Arya Jayadrata melangkah keluar, jubah perangnya tersapu angin senja yang gelap. Di matanya menyala kebanggaan: Arjuna telah gagal. Dunia menyaksikan seorang pangeran Kuru berdiri dengan dada tegak—keyakinan telah menyelamatkannya dari takdir.
Ia mendongak, menatap langit yang muram.
“Aku masih hidup!” serunya lantang. “Arjuna telah bersumpah, dan kini gagal menepatinya! Apakah ini ksatria besar kalian?”
Tapi di saat itulah, Prabu Kresna menoleh ke Arjuna, suaranya rendah, namun nyaring menembus dada:
“Itu dia. Sekarang. Jangan ragu.”
Arjuna menarik busurnya. Gandiva merintih di tangannya, dan Pasopati—panah para dewa, senjata pemutus nyawa—bergetar dalam kekuatan yang nyaris tak bisa ditahan.
Ia tidak berteriak. Ia tidak mengutuk. Hanya mata yang berbicara, memancang Jayadrata seolah seluruh dunia mengunci sasaran itu.
Dalam satu hembusan napas, panah Pasopati melesat, menoreh udara seperti kilat tak bermusim. Jayadrata bahkan belum sempat merunduk ketika lehernya terbabat sebersih cahaya memutus malam.
Kepalanya melayang ke udara, terangkat sejenak di bawah langit yang masih kelam, lalu jatuh… hening. Tubuhnya menyusul sesaat kemudian, berlutut… lalu rebah tak bernyawa.
Dan seketika itu pula, Kresna memutar kembali Cakra Beskara. Cahaya matahari kembali memancar, menyinari tubuh Jayadrata yang kini hanya bayangan di atas tanah.
Di balik medan, prajurit Kurawa gemetar. Pandawa terpaku dalam keheningan yang baru saja menyaksikan sumpah seorang ksatria ditepati, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebenaran yang tajam seperti panah Pasopati itu sendiri.
Begitu tubuh Jayadrata tergolek tak bernyawa, angin Kurukshetra kembali berembus—dingin, getir, dan berat. Kematian yang datang lewat panah Pasopati bukan hanya mengakhiri sumpah Arjuna, tetapi juga membuka lembaran baru dalam dendam dan darah.
Dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah berat. Tanah seolah bergemuruh. Resi Sapwani Wijawastra, ayah angkat Jayadrata, turun ke medan perang. Rambutnya putih panjang, jubahnya berkibar dalam angin, dan sorot matanya menyala seperti api yang dikobarkan oleh kehilangan.
Ia bukan sekadar seorang resi. Ia adalah seorang guru agung, penjaga garis dharma, dan sekarang: ayah yang kehilangan anak.
“Arjuna,” serunya lantang, suaranya menggema menembus langit, “engkau telah melukai hatiku. Engkau telah merampas cahaya dari rumahku.”
Arjuna tidak menjawab. Ia menunduk sejenak, bukan karena takut, melainkan karena menghormati usia dan kedalaman jiwa Sapwani. Tapi Kresna hanya menoleh sedikit, dan berseru tenang:
“Ia datang dengan api. Maka bersiaplah dengan cahaya.”
Pertarungan pun dimulai. Sapwani melesat seperti petir tua, melepaskan mantra dan senjata sakti bertubi-tubi. Langit kembali bergetar. Tapi Arjuna, yang kini seperti telah dibersihkan oleh kemarahan dan kesedihan, bertarung dengan ketenangan yang menyerupai ketepatan ilahi.
Gandiva menderu. Panah-panahnya bukan sekadar senjata, tetapi jawaban atas segala kebencian dan kegetiran. Sapwani bertahan, melepaskan Astra demi Astra, namun satu demi satu ditangkis, dibelah, dikembalikan oleh kekuatan Arjuna yang kini tak tertahan.
Satu panah terakhir—dengan mantra Brahmastra yang hanya digunakan saat perlu—meluncur dari Gandiva, menghantam dada Sapwani yang sudah melemah. Resi agung itu berlutut, tangannya masih mencoba menggenggam tanah.
“Jayadrata, anakku… semoga jalanmu tenang,” gumamnya, lalu roboh.
Langit Kurukshetra kini merah keemasan. Hari belum usai, tapi sudah terlalu banyak yang hilang.
Langit mulai gelap. Bukan karena malam telah tiba, tetapi karena awan-awan hitam menggantung rendah, seakan menandai sesuatu yang agung akan gugur.
Di antara kabut dan debu perang yang belum usai, terdengar denting logam bersahutan—Gatotkaca, raksasa angkasa, putra Bima dari bangsa raksasa Pringgandani, melayang di udara seperti bayangan dewa.
Tubuhnya menjulang tinggi, matanya menyala, dan petir seakan menyambut setiap langkah kakinya di langit.
Di bawahnya, Adipati Karna, sang pemanah agung dari Angga, berdiri tegak, memandangi Gatotkaca yang terus membombardir dari udara.
Gatotkaca tidak hanya menyerang, ia menantang, menggoda, memancing murka.
“Kau simpan panahmu untuk Arjuna, Karna? Tak sudi kau hunuskan untuk anak Bima?”
Karna diam. Tapi dalam diam itu, wajahnya mengeras. Rasa kesal menumpuk. Serangan Gatotkaca dari atas terus-menerus menyulitkannya. Pasukan Kurawa menjadi kacau. Panah-panah Karna tak lagi mampu mengejar tubuh raksasa yang menari di langit.
Lalu, ia melakukannya.
Satu hentakan kaki. Satu embusan napas. Tangannya menggapai tabung senjata, dan dari sana ditariklah… Kunta Wijayandanu.
Senjata suci itu berkilau seperti matahari kecil, senjata pamungkas yang hanya boleh dipakai sekali, yang ia simpan untuk Arjuna.
Tapi kesabaran Karna telah habis. Dalam sekejap, senjata itu dilepaskan.
Gatotkaca, yang sejak tadi menari di langit, melihat kilau itu. Ia tahu. Ia tahu benar apa itu. Matanya melebar, tapi tidak karena takut.
Ia tersenyum.
Lalu ia terbang lebih tinggi, naik menembus awan, menjemput senjata itu dengan dada terbuka. Ia tahu, jika Kunta Wijayandanu digunakan hari ini, maka Arjuna akan hidup esok hari.
Di antara awan-awan yang suram, sesosok cahaya tampak membantu senjata itu meluncur tepat ke sasaran—Arya Kalabendana, paman tercinta Gatotkaca yang telah lama gugur, menampakkan diri sejenak untuk memastikan takdir benar-benar terjadi.
DOR!
Langit bergetar. Tubuh Gatotkaca meledak dalam cahaya menyilaukan, pecah jadi ribuan keping cahaya, lalu perlahan jatuh dari langit, bagaikan bintang yang runtuh.
Satu demi satu, prajurit Pandawa dan Kurawa mendongak. Mereka terdiam. Bahkan pasukan Kurawa yang tadi bersorak, mendadak bungkam.
Hanya Karna yang berdiri sendiri. Tangannya masih mengepal, matanya menerawang ke tempat Gatotkaca terakhir terlihat. Dalam dadanya, ada kemenangan—tapi juga kehilangan.
Ia tahu, panah itu bukan untuk Gatotkaca.
Suasana Kurukshetra masih diselimuti keheningan setelah tubuh Gatotkaca jatuh seperti bintang runtuh. Tapi waktu tak memberi ruang untuk berduka lama. Di sisi lain medan laga, dua ksatria tengah terlibat pertarungan berdarah dan penuh dendam: Arya Setyaki, panglima dari Dwaraka, berhadapan dengan Arya Burisrawa, pangeran tua dari bangsa Kurawa, sahabat lama Resi Durna.
Keduanya terluka. Napas tersengal. Pedang dan gada telah patah, dan kini pertempuran berlanjut dengan tangan kosong dan kemauan baja. Burisrawa, bertubuh tinggi besar, dengan mata yang menyala karena kemarahan, mengayunkan tinjunya ke wajah Setyaki, membuat sang ksatria muda terhuyung dan terjatuh.
Burisrawa menarik belatinya.
“Waktu untukmu telah habis, Setyaki,” geramnya.
Setyaki mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Di kejauhan, Prabu Kresna melihat semuanya, dan tatapannya tajam beralih ke Arjuna.
“Apakah kamu masih mampu?” tanyanya, tenang namun menusuk.
Arjuna, masih terdiam karena duka Abimanyu dan kematian Gatotkaca, menunduk.
“Aku… aku tak tahu, Kresna.”
Kresna tak membalas. Ia mengangkat sehelai rambut panjang dari ikat pinggangnya, menahannya di antara dua jari.
“Jika kamu benar-benar tak tahu,” katanya, “belahlah ini. Jika Gandiva dan hatimu masih satu, rambut ini akan terbelah. Jika tidak, maka kau bukan lagi Arjuna yang kubawa ke medan dharma ini.”
Arjuna terdiam. Angin berhenti. Lalu perlahan ia menarik Gandiva.
Plak!
Panah itu meluncur, membelah rambut dengan presisi sempurna. Tapi tidak berhenti di situ. Panah itu terus melesat seperti dituntun oleh dewa, dan dalam sekejap menghantam kepala Arya Burisrawa dari samping, menghentikan langkah kematiannya atas Setyaki.
Ksatria tua itu jatuh berlutut, masih dengan tangan terangkat. Tapi sebelum roboh, ia sempat menoleh ke arah Arjuna, dan… tersenyum kecil.
“Tepat… seperti dulu,” bisiknya pelan.
Tubuhnya tumbang, dan debu Kurukshetra menyambutnya sebagai bagian dari sejarahnya.
Setyaki bangkit, menatap Arjuna dari jauh dan memberi hormat dalam diam. Ia tahu, nyawanya barusan dibayar oleh kecepatan dan keteguhan seorang sahabat lama.
Kini, perang kembali senyap sesaat. Tapi tidak untuk lama, karena malam belum tiba, dan darah belum kering.
Di antara bayang senja dan abu-abu yang menggantung di langit Kurukshetra, tanah medan laga belum kering oleh darah, namun waktu seolah meregang, memberi jeda bagi sebuah kehadiran yang tidak disangka.
Dari sisi barat medan perang, seorang ksatria muda muncul dengan langkah mantap. Kulitnya hitam kebiruan seperti baja Pringgandani, matanya menyala namun tenang, dan dari rambutnya yang terurai melambai bendera kecil berwarna merah darah. Ia mengenakan baju zirah warisan raksasa dan dewa. Di punggungnya tergantung tiga buah anak panah yang konon hanya itulah yang ia perlukan untuk memusnahkan seluruh pasukan dunia.
Ia adalah Arya Barbarika.
Putra dari Gatotkaca dan Dewi Ahilawati, cucu Bima, darah Pandawa, namun datang ke Kurukshetra bukan sebagai pembela keluarga—melainkan penunaian dharma yang telah ia ikrarkan jauh-jauh hari.
Ia telah bersumpah, kepada siapa pun yang paling lemah, ia akan berdiri di pihak mereka.
Dan hari itu, yang paling lemah—adalah Kurawa.
Prajurit Kurawa memandangnya heran, namun juga takut. Sebagian dari mereka bahkan mundur selangkah ketika Barbarika menapakkan kaki ke tengah medan. Ia tidak perlu diperkenalkan. Senjata-senjatanya bersinar sendiri. Panahnya seakan berdenyut seperti jantung bumi.
Di kejauhan, Prabu Sri Kresna memperhatikannya dari atas kereta Arjuna. Tatapannya tenang namun menyelidik.
“Ia datang,” ujar Kresna pelan. “Seperti yang telah kita perhitungkan.”
Arjuna menoleh, terkejut.
“Ke pihak Kurawa?”
Kresna mengangguk. “Ia tidak berpihak pada nama, melainkan pada keseimbangan.”
Para Panglima Kurawa mulai menghampiri Barbarika, tapi ia hanya mengangkat tangan.
“Aku tak tunduk pada perintah manusia. Aku hanya menjalankan sumpahku: berpihak pada yang tertindas. Hari ini, itu adalah kalian.”
Resi Durna menyipitkan mata, mengenal aura sakti dari pemuda itu. “Tapi kau darah Pandawa… cucu Bima.”
“Benar,” sahut Barbarika. “Dan kakekku telah gugur hari ini demi menyelamatkan pamannya. Aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga keseimbangan. Karena bila aku turun sepenuhnya, tak akan ada sisa perang ini yang hidup.”
Dan dengan itu, ia mencabut satu dari tiga panahnya, menancapkannya ke tanah.
Awan berguncang. Tanah bergetar. Bahkan Kresna sendiri menarik napas dalam-dalam.
“Jika dia melepaskan panah keduanya…” gumam Kresna, “bahkan aku pun tak bisa menjamin nasib Kurukshetra.”
Tapi Barbarika tidak melepaskannya. Ia hanya menancapkan satu, cukup untuk mengikat sebagian besar pasukan lawan dalam lingkaran energi, menahan mereka dalam perhitungan keseimbangan dharma.
Hari keempat belas pun ditutup dengan matahari kembali muncul dari balik Cakra Beskara milik Kresna, menandai bahwa janji Arjuna telah terpenuhi, dendam telah dibayar, darah telah tertumpah, dan kematian Gatotkaca—yang hari itu dikubur bersama langit—telah membuka babak baru dalam perang suci ini.
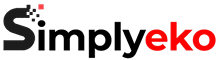
Leave a Reply