
Kurukshetra membentang laksana dada bumi yang terbuka: luas, kering, dan kosong sejauh mata memandang. Tanah ini bukan sekadar lapangan; ia adalah lembaran sejarah yang siap ditulisi dengan darah, senjata, dan kehormatan. Sejak malam terakhir sebelum perang, angin di dataran itu membawa aroma debu bercampur kecemasan. Burung enggan terbang rendah. Hening terlalu pekat untuk dini hari.
Belum ada mayat. Belum ada teriakan. Belum ada ratapan. Tapi semua tahu, saat mentari menyembul dari timur, dunia takkan lagi sama.
Kurukshetra—yang dalam bahasa tua berarti “lapangan Kuru”—telah dipilih bukan karena letaknya, melainkan karena kemuliaannya. Di sinilah para resi turun-temurun menjejakkan kaki. Di sinilah para leluhur Pandawa dan Kurawa dahulu bertapa, mencari petunjuk dewa-dewa untuk menegakkan kebenaran. Kini, anak-anak mereka berdiri di atas tanah yang sama, namun bukan untuk memohon, melainkan untuk merebut.
Hari itu, bahkan sebelum fajar membuka kelopaknya, dua tokoh tua berjalan beriringan di tengah lapangan: Resi Bisma Dewabrata dan Resi Arya Seta. Yang satu membawa sumpah yang telah menjadi tulang, yang satu membawa hikmah yang sudah menjadi cahaya.
Mereka tidak berseteru. Tidak saling menghunus senjata. Mereka berbicara, sebagaimana para bijak berbicara sebelum zaman hancur di tangan orang muda.
“Bharatayudha harus dilakukan secara ksatria,” ujar Arya Seta, suaranya berat oleh beban masa depan.
“Dan bukan menjadi medan pengkhianatan,” sahut Bisma. Sorot matanya tajam, tapi lembut.
Lalu mereka menetapkan hukum. Sebuah perjanjian di bawah langit terbuka, yang kelak akan dikenang sebagai Dharmayudha—perang yang menjunjung dharma di atas dendam.
Matahari harus menjadi gong waktu: perang dimulai saat ia terbit, dan harus berhenti saat ia tenggelam.
Prajurit yang menyerah tak boleh dibunuh.
Yang tak bersenjata tak boleh disentuh.
Wanita, penabuh genderang, pembawa panji, perawat luka—semuanya harus dijaga.
Gada tak boleh memukul di bawah pinggang.
Panah tak boleh ditembakkan ke punggung.
Pertempuran harus satu lawan satu. Tidak ada keroyokan. Tidak ada tipu daya.
“Aku tahu aturan ini akan dilanggar,” Bisma berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. “Tapi lebih baik kita menetapkan dharma, daripada membiarkan dunia runtuh tanpa arah.”
Arya Seta mengangguk, tak berkata apa-apa. Dalam diamnya, ada restu dan kesedihan yang tak terucap.
Lalu mereka berpisah.
Langit mulai merah. Suara roda kereta dari arah timur dan barat mulai bersahutan. Tanah bergetar. Genderang dipukul. Panji-panji berkibar, melawan angin yang kini tak lagi netral. Angin pun seperti memilih sisi.
Dari timur, datanglah Pandawa. Lima bersaudara, berdiri bukan hanya sebagai ksatria, tapi juga sebagai anak-anak dari luka dan pengasingan.
Yudistira memimpin di depan, tenang namun tak sepi dari beban. Wajahnya tampak seperti tanah itu sendiri: tabah, pasrah, namun dalam.
Bima datang seperti petir, menggenggam gada Rujakpala yang siap memecah tulang dan sumpah palsu.
Arjuna berdiri di atas keretanya, bersama Kresna, sang kusir yang tak kalah dari dewa. Wajah Arjuna tenang, tapi matanya tajam seperti anak panah yang belum dilepaskan.
Nakula dan Sadewa, si kembar dari darah Dewi Madrim, adalah kesunyian yang menyimpan badai.
Dari barat, muncul barisan Kurawa. Seolah tak ada habisnya. Mereka datang laksana gelombang hitam.
Di ujung barisan, berdiri Duryudana, penuh percaya diri dan marah yang telah dibina selama bertahun-tahun. Di belakangnya, Karna berdiri diam seperti tombak tertanam, sementara Drona, guru yang kini menjadi jenderal Kurawa, mengatur pasukan dengan dingin.
Aswatama membawa kebrutalan yang belum tumbuh penuh.
Salya dan Sengkuni menyusul, membawa sejarah rumit dan luka yang belum dijahit.
Semua telah datang. Semua telah memilih.
Di tengah medan, para pemukul genderang berdiri siap. Para pembawa panji memegang kain yang telah dijahit berhari-hari. Para perawat membawa kantong obat, belum tahu siapa yang pertama akan mereka rawat.
Kurukshetra menahan napas. Tanah itu tidak memihak. Ia tidak bicara. Tapi setiap batu dan butir pasirnya telah mencatat sumpah dan tekad manusia.
Dalam sekejap, langit terang sepenuhnya.
Sangkakala ditiup. Suaranya panjang, seperti bunyi dari mulut dunia.
Lalu, Bharatayudha pun dimulai.
Delapan belas hari dan delapan belas malam akan berlalu. Akan ada darah. Akan ada pengkhianatan. Akan ada ksatria yang gugur bukan karena kalah, tapi karena dharma dilanggar. Akan ada senjata sakti yang digunakan tidak sesuai aturan. Akan ada sumpah yang patah, dendam yang menelan akal, dan air mata yang mengalir bukan hanya dari manusia, tapi juga dari langit.
Namun hari itu, hari pertama, segalanya masih utuh. Segalanya masih bisa berubah.
Dan di sela-sela gemuruh kereta dan teriakan ksatria, Kurukshetra—tanah tua yang telah melihat terlalu banyak—berbisik dalam diam:
“Wahai keturunan Kuru, bertarunglah jika itu jalanmu. Tapi jangan lupakan satu hal:
Di tanah ini, dharma harus berdiri lebih tinggi dari kemenangan.”
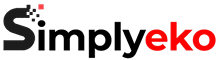
Leave a Reply