
Kabut pagi menyelimuti dataran Kurukshetra, tipis seperti tirai yang mengaburkan takdir. Di kejauhan, genderang perang berdentang—keras dan berulang, seperti detak jantung raksasa yang tengah bersiap mengguncang dunia. Kedua pihak, Pandawa dan Kurawa, berdiri dalam formasi mereka: supit urang yang menjepit dari dua sisi, melawan tempurung baja formasi kura-kura, Kurmabyuha.
Semangat membara dari kedua belah pihak. Mata para ksatria berkilat seperti ujung tombak yang siap ditancapkan ke dada siapa pun yang menghalangi.
Di tengah medan itu, dua sosok maju ke depan. Arya Drestajumena dari pihak Pandawa dan Prabu Salya dari pihak Kurawa saling menatap tajam. Drestajumena, putra raja Pancala, adalah pembawa dendam terhadap para Kurawa, sementara Salya, raja Madra, dikenal karena siasat dan kekuatan magisnya yang licik.
Teriakan perang belum sepenuhnya padam ketika pertarungan mereka meledak. Pedang beradu, tombak ditepis, siasat dan kekuatan dipertarungkan tanpa jeda. Tapi Salya bukan ksatria biasa. Dengan kekuatan sihir yang halus, ia menggetarkan udara, mengaburkan pandangan, mengacaukan arah serangan Drestajumena. Arya Pancala itu mulai kewalahan. Ia memutar-mutar tombaknya dalam gelap ilusi, tak tahu lagi di mana musuh berada.
Hampir saja ia jatuh ketika tiba-tiba terdengar teriakan keras dari barisan Pancala. “Pahlawan Pancala! Ingat sumpahmu!”
Suara itu menggema seperti lonceng kesadaran. Drestajumena terdiam sekejap. Ia mengingat ayahnya yang gugur, negerinya yang diinjak-injak. Ia menancapkan tombaknya ke tanah, menarik napas panjang, lalu membebaskan pikirannya dari kabut sihir. Dalam sekejap, matanya kembali jernih—dan ia menangkis serangan Salya dengan telak. Pertarungan berlanjut sengit, namun kini seimbang.
Sementara itu, di sisi lain medan perang, badai mulai bergerak. Bima, sang putra Bayu, maju tanpa ragu. Pasukan gajah yang dikirim Duryudana maju bagai dinding hidup, mengguncang bumi dengan tiap langkah.
Namun Bima bukan ksatria yang bisa dihentikan dengan barisan. Ia melompat ke depan, gada Rujakpala terangkat tinggi. Dengan raungan seperti petir, ia menghantam tanah—dan tubuh gajah-gajah itu berguling, patah, hancur.
“Bukan kalian yang kucari,” gumam Bima di antara debu dan darah. Ia berlari menerobos ke tengah pasukan Kurawa, matanya memburu satu nama: Duryudana.
Namun sebelum sampai ke sana, sembilan orang menghadangnya. Sembilan adik Duryudana—Durmuka, Durmandaka, Durnandaka, Durpramata, Durprasadarsa, Dursaha, Dursara, Dursaya, dan Durta.
“Langkahi kami dulu, Bima!” seru Durmuka.
Bima hanya tersenyum dingin. “Sudah kubilang, ini bukan hari kalian.”
Dan badai pun pecah.
Satu per satu, adik-adik Duryudana roboh. Tubuh mereka beterbangan, darah menyiram tanah, dan suara gada yang menghantam tubuh terdengar seperti gendang maut. Pertempuran itu bukan pertarungan, melainkan penumpasan.
Saat matahari merangkak ke barat dan terompet mundur ditiup dari kedua belah pihak, suasana di kubu Kurawa suram dan berduka. Duryudana sendiri berdiri lama menatap medan perang, sebelum akhirnya melangkah menuju tenda Resi Bisma.
Ia masuk tanpa suara. Matanya merah, wajahnya tegang. Suaranya pelan, namun getir.
“Kakek… mengapa mereka begitu perkasa hari ini? Mengapa sembilan saudaraku gugur seperti rumput disabit?”
Resi Bisma menatapnya dalam-dalam, duduk tenang di atas tikar perang.
“Karena mereka bertempur dengan kebenaran di hati mereka, Nak. Pandawa tidak menginginkan perang ini, tapi mereka menjalani takdirnya dengan jujur. Kebenaran memberi kekuatan yang tak kau miliki.”
Duryudana mengepalkan tangan. Matanya bergetar. Dalam hatinya, kata-kata itu seperti tusukan—seolah Bisma lebih memihak Pandawa.
“Jadi menurutmu… aku harus menyerah?”
“Damai bukan kekalahan, Duryudana. Itu kebijaksanaan.”
Hening panjang menyelimuti tenda.
Duryudana akhirnya berdiri. Matanya kini dingin.
“Jika damai berarti aku harus menunduk di kaki musuhku, maka lebih baik aku jatuh di medan perang.”
Ia keluar dari tenda tanpa menoleh.
Resi Bisma menatap ke tanah, napasnya berat. “Dan perang pun terus berlanjut,” gumamnya.
Malam turun perlahan di atas Kurukshetra. Angin mengangkat aroma darah dan abu. Ksatria lelah menarik nafas panjang, tapi perang belum selesai. Tidak esok, tidak lusa. Masih panjang jalan menuju akhir. Namun di hari keempat itu, kebenaran mulai tampak—di tengah gada, kabut, dan kebodohan seorang raja yang tak mau belajar dari nasihat orang suci.
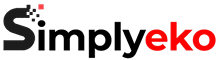
Leave a Reply