
Kabut tebal menggantung di atas medan Kurukshetra, seolah langit enggan memperlihatkan wajahnya kepada bumi yang penuh luka. Embusan angin membawa aroma besi darah dan abu dupa dari perabuan semalam. Tanah bergetar pelan, bukan karena derap kuda, melainkan karena beban takdir yang kian berat dipikul bumi suci ini.
Di sisi timur, cahaya matahari nyaris tak mampu menembus tirai kelabu yang menyelimuti langit. Di atas keretanya, Prabu Sri Kresna memandangi cakrawala tanpa suara. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan rencana yang akan mengubah arah pertempuran. Di sebelahnya, Arjuna membisu. Keguguran Abimanyu masih menyisakan duka, namun kini sorot matanya telah mengeras. Tidak ada lagi ruang untuk ragu.
Di kubu Kurawa, Resi Durna duduk bersila di depan senjatanya. Rambut dan janggut putihnya diterpa angin pagi. Matanya terpejam. Ia baru saja selesai membaca mantra. Meski tubuhnya gagah, jiwanya mulai letih. Ia guru para pangeran, kini terpaksa memimpin salah satu pihak saling membunuh. Namun demi dharma yang ia yakini, ia tetap berdiri.
Tak jauh dari sana, Prabu Duryudana bersiap di sisi barat. Kini hanya kemarahan dan keputusasaan yang memandunya. “Hari ini,” gumamnya, “Resi Durna akan memecah barisan Pandawa sampai tercerai-berai.”
Namun di antara semuanya, hanya satu sosok yang berdiri paling tenang, meski pikirannya mendidih: Arya Drestajumena, Senapati Pandawa. Di tangannya masih terbayang darah ayahnya, Prabu Drupada. Dan di hadapannya kini berdiri sang pembunuh: mantan guru yang dulu pernah ia hormati—Resi Durna.
Di tenda perkemahan Pandawa yang sepi, api unggun pagi hanya bergetar kecil tertiup angin. Prabu Sri Kresna berdiri di tengah para Pandawa. Punggungnya lurus, sorot matanya tembus ke masa depan. Tak ada senyum di wajahnya kali ini. Yang tersisa hanyalah ketegasan seorang dewa pemutus takdir.
“Resi Durna,” ujarnya perlahan, “tidak akan berhenti sebelum kehancuran benar-benar menggenangi Kurukshetra. Ia adalah benteng terakhir kekuatan Kurawa. Tapi… ada satu hal yang bisa meruntuhkan keyakinannya.”
Bima melangkah ke depan. “Katakan saja, Kresna. Aku akan menghancurkannya seperti kubunuh ratusan prajurit kemarin.”
Kresna mengangguk. “Bukan kekuatan yang kubutuhkan darimu, Bima. Tapi suara.”
“Suara?” tanya Nakula dan Sadewa hampir bersamaan.
“Ya,” Kresna menjawab. “Bima, hari ini kau harus membunuh seekor gajah bernama Aswatama. Setelah itu, kau harus berteriak sekeras-kerasnya bahwa ‘Aswatama telah gugur di medan Kurukshetra’.”
Semua terdiam.
Bima tertawa pelan. “Licik, tapi indah. Akan kulakukan.”
Namun bukan Bima yang menjadi penghalang siasat ini. Dari sisi lain ruangan, Prabu Yudhistira menunduk. Ia tidak berbicara, tidak langsung menolak. Tapi udara di sekitarnya terasa lebih berat.
“Yudhistira,” Kresna berkata pelan, suaranya bergetar tapi mantap, “dengarkan aku. Kadang-kadang, satu kebohongan bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Kau, yang selama hidupmu tidak pernah berdusta, hari ini hanya akan berkata setengah kebenaran.”
Yudhistira menatap Kresna, matanya lembut namun penuh beban. “Aku bersumpah tidak akan berbohong… tapi hari ini, bila ini memang jalan dharma… aku akan mengatakannya dengan suara pelan, dan membiarkan semesta menyaring bagian akhirnya.”
Kresna menaruh tangan di pundaknya. “Kebenaran hari ini bukanlah suara yang keras, Yudhistira. Tapi niat yang suci.”
Dan saat itu juga, takdir mulai bergulir seperti kereta perang yang dipacu menuju medan maut.
Di tengah medan Kurukshetra yang basah oleh darah dan patahan senjata, Resi Durna berdiri kokoh di atas keretanya. Matanya menyapu garis tempur yang semakin semrawut. Sementara itu, teriakan keras menggema dari sisi selatan medan laga.
“Aswatama gugur!”
Suara Bima. Lantang dan meyakinkan.
Resi Durna seketika menegakkan tubuhnya. Wajahnya yang keriput tampak membeku. Panah di tangannya gemetar.
“Tidak mungkin…” gumamnya. “Aswatama… putraku…”
Ia memejamkan mata, seolah mencoba menolak gema kata-kata itu. Tapi suara itu kembali menggema, seakan Kurukshetra sendiri bersuara: “Aswatama gugur!”
Resi Durna turun dari keretanya. Langkahnya cepat, tubuhnya yang tua tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Ia berjalan ke arah tenda Pandawa. Sesuatu dalam dirinya tahu… hanya suara mereka yang bisa meyakinkannya.
Sesampainya di sana, ia langsung menemui Bima.
“Bima…” suaranya dalam, berat, “katakan padaku, putraku Aswatama… gugurkah ia?”
Bima menatapnya lurus-lurus. “Benar. Aswatama telah gugur.”
Resi Durna menarik napas dalam. Namun ia masih belum sepenuhnya percaya.
Ia lalu beralih pada Arjuna, murid yang dulu diajarkannya dengan cinta seperti kepada putra sendiri.
“Arjuna… kau yang paling kukenal. Jangan beri aku dusta. Apakah benar… Aswatama, putraku, telah gugur?”
Arjuna, dengan nada berat dan duka dalam suaranya, menjawab, “Ya, Guru. Aswatama telah gugur.”
Tapi masih, hati sang guru belum bisa menerima. Masih ada satu suara yang lebih suci dari semua suara. Satu suara yang tak pernah berdusta.
Resi Durna berbalik dan menatap Puntadewa.
“Yudhistira… kau, raja suci… katakan padaku. Benarkah… Aswatama, putraku, telah gugur?”
Yudhistira menatap tanah. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik:
“Aswatama… gugur.”
Dan di ujung suaranya, begitu pelan hingga hanya langit yang mendengar, ia tambahkan: “…gajah.”
Resi Durna mengangguk perlahan. Di dadanya, sesuatu pecah. Ia mundur dua langkah, melepaskan busur dari bahunya, dan menjatuhkannya ke tanah. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut… tapi karena duka yang dalam tak terperi.
Ia duduk bersila di atas medan perang. Memejamkan mata. Tangan bertangkup di dada.
“Jika takdir telah bicara, maka biarlah aku menyerah pada waktu…”
Dan saat itulah, dari balik debu dan asap, Drestajumena datang.
Diam-diam, tegas, seperti bayangan dendam yang dipelihara sejak kematian ayahnya, Prabu Drupada.
“Resi Durna…” ucap Drestajumena lirih.
Resi Durna membuka matanya. Ia menatap Drestajumena, tak ada kebencian, hanya pengertian. “Anakku, lakukanlah apa yang harus kau lakukan.”
Drestajumena tak menjawab. Ia mencabut pedang dari pinggangnya.
Dalam satu kilatan, kepala sang guru terlepas dari tubuhnya dan jatuh perlahan ke tanah, seolah waktu ikut menunduk hormat.
Angin mendadak berhenti. Debu di medan laga pun seakan membeku.
Kereta Puntadewa yang sebelumnya selalu melayang beberapa inci dari tanah, perlahan turun dan menyentuh bumi. Para Pandawa diam menatap kejadian itu, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang Raja suci telah mengucapkan kata yang kabur dari kebenaran mutlak.
Di sisi lain, upacara pembakaran jenazah Resi Durna dilakukan dengan sunyi. Api menyala pelan, langit mendung menggantung. Hadir dalam upacara itu Arya Widura, sang penasehat tua yang matanya sembab tapi tak meneteskan air mata. Para sesepuh negara Hastina berdiri berjajar, berdoa dalam diam. Prabu Duryudana dan Kurawa lainnya hanya melihat dari kejauhan, hati mereka gamang antara kehilangan dan kehancuran yang semakin dekat.
Hari kelima belas berakhir dalam sunyi. Dalam bayang api unggun dan bau dupa kematian. Tidak ada kemenangan. Tidak ada sorak. Hanya satu suara yang menggema dalam hati tiap ksatria:
Dharma… telah menempuh jalan yang getir.
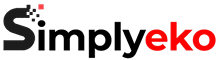
Leave a Reply