
Fajar kesepuluh Bharatayudha tak menyingsing dengan cerah. Langit berselimut kelabu pucat, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di hari itu. Angin bertiup lirih, membawa debu dan aroma besi, darah, dan doa yang belum terjawab.
Di sisi Pandawa, Prabu Sri Kresna berdiri memandangi langit pagi. Ia tidak berbicara, tapi matanya memantulkan kesadaran akan sesuatu yang besar. Sementara itu, Pandawa menyusun formasi Diradameta—gajah mengamuk yang menggempur dari segala penjuru. Kurawa membalasnya dengan Kraunchabyuha—formasi bangau maut yang menusuk dari ujung ke ujung.
Dari sisi Kurawa, muncul Prabu Bogadenta, berdiri gagah di atas punggung Gajah Murdanikung, dengan Dewi Murdaningsih, istri sekaligus saisnya yang setia, di sisi. Mereka bukan hanya pejuang, tapi pasangan yang bersumpah untuk bertarung dan gugur bersama. Gajah mereka menderap ke tengah medan dengan langkah seberat gunung, membuat tanah Kurukshetra gemetar.
Menghadapi mereka adalah Arjuna, sang pemanah agung. Ia tidak tergesa. Ia tahu ini bukan sekadar pertempuran, melainkan perpisahan agung dua jiwa mulia. Anak panahnya pertama tak langsung membunuh, tetapi membuka ruang di antara siasat dan rasa hormat. Tapi pada akhirnya, gajah roboh, panah menembus dada Bogadenta dan Murdaningsih sekaligus. Mereka jatuh—dalam pelukan, dalam cahaya, dalam ketenangan.
Langit sejenak hening.
Namun, Kresna tahu: itu bukan akhir hari ini.
Ia memanggil Dewi Srikandi.
“Waktunya telah datang,” ujar Kresna pelan, “untuk menutup lingkar dendam yang belum selesai.”
Srikandi, titisan Dewi Amba, menatap jauh ke medan di mana berdiri Resi Bisma Dewabrata. Ia bukan sekadar lawan. Ia adalah luka lama yang belum tersembuhkan oleh waktu. Tapi hari ini, luka itu harus dihadapi, bukan dengan amarah, tapi dengan panah keadilan.
Ia melangkah ke medan laga, dan langit terasa menahan nafas. Di hadapannya, Bisma berdiri tegak, jubahnya putih, mata sayunya memandangi Srikandi—dan dalam wajahnya, ia melihat Amba. Bukan sekadar perempuan yang pernah mencintainya, tapi takdir yang menuntut balasan.
Ia tidak mengangkat senjata. Ia hanya membuka dada.
Panah Srikandi melesat. Pertama satu, lalu sepuluh, lalu seratus. Tubuh Bisma tertusuk di setiap bagian, namun ia tetap berdiri. Lalu perlahan ia berlutut, dan jatuh—bukan ke tanah, tapi menggantung di atas panah-panah itu, seolah bumi tak sanggup menampungnya.
Sangkakala ditiup. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menghormati.
Seluruh pasukan, baik Pandawa maupun Kurawa, membisu. Mereka menyaksikan, seorang mahaguru, pemegang dharma, telah tumbang bukan karena kalah… tapi karena memilih untuk menyerah pada kebenaran.
Arya Dursasana, panik, segera berlari membawa tilam bersulam emas dari istana Hastina.
“Guru! Kami bawakan alas terbaik! Prabu Duryudana memerintahkan—”
Tapi Bisma menahan tangannya, dan tersenyum lemah.
“Tilam seorang ksatria bukanlah emas dan permata, Dursasana… tapi tanah, luka, dan kehormatan.”
Ia menoleh ke arah Arjuna.
“Partha… berikan aku bantal prajurit.”
Arjuna membungkuk dalam, lalu menarik busurnya. Tiga anak panah ditancapkan ke tanah, dan dengan lembut ia menidurkan kepala Resi Bisma di atas ujungnya. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bergerak.
Semua menunduk.
Bisma membuka matanya. Kresna sudah berdiri di sisinya.
“Waktuku telah datang,” ucap Bisma lirih.
“Namun tidak untuk mengakhiri hidup. Aku diberi anugerah untuk memilih saat ajalku… dan aku memilih untuk menunggu hingga perang ini usai. Biarkan aku menjadi saksi. Biarkan aku menyaksikan di mana kebenaran akhirnya akan berpihak.”
Ia menatap langit, lalu menutup mata, memanjatkan doa pada Sang Hyang Manikmaya agar memberinya umur hingga akhir Bharatayudha.
Kresna menunduk, menjawab dengan lirih:
“Permintaanmu akan dikabulkan. Kau bukan hanya ksatria, Bisma… tapi cahaya dalam perang yang dibutakan oleh ambisi.”
Hari itu, perang dihentikan sementara.
Bukan karena kelelahan.
Bukan karena kekalahan.
Tapi karena dunia perlu waktu untuk mencerna kejatuhan seorang yang begitu agung, hingga bahkan panah pun tak sanggup menjatuhkannya ke tanah.
Bisma tidak mati. Tapi ia telah menyerahkan hidupnya pada dharma.
Dan di langit Kurukshetra, matahari akhirnya tampak—bukan sebagai kemenangan… tapi sebagai cahaya yang memberi waktu untuk hening.
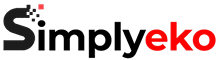
Leave a Reply