
Matahari pagi menggantung redup di langit Kurukshetra, seolah enggan menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Debu tipis mengepul pelan di medan perang, menandai persiapan dari dua formasi raksasa yang saling berhadapan—Ardhacandrabyuha dari pihak Pandawa, melengkung seperti bulan sabit, dan Garudawyuha dari pihak Kurawa, kokoh dan tajam bagaikan cakar elang.
Di tengah riuh perang yang belum meletus, Arjuna duduk hening di atas kereta perangnya. Panah-panah tersusun rapi di tabung, Gandiva menggantung di bahunya, tapi dadanya seakan memberat.
“Di sana dia,” gumam Arjuna pelan. Di ujung barisan Kurawa berdiri seorang tua, berjanggut putih, memegang busur besar yang tak pernah meleset. Resi Bisma. Kakeknya. Pengasuh masa kecilnya. Sumber banyak tawa dan cerita lama.
Ingatan menyelinap tanpa diundang—waktu kecil, ia pernah tertidur di pangkuan Bisma, tertawa saat mereka bermain kejar-kejaran di taman istana Hastinapura. Bisma menggendongnya ketika ia menangis karena lututnya lecet. Kasih itu nyata. Dan kini, ia harus mengarahkan anak panah ke dada orang yang pernah memeluknya erat.
“Arjuna,” suara lembut namun tegas membuyarkan lamunannya. Prabu Sri Kresna, yang berdiri di sisi kereta, menatapnya penuh sorot tajam. “Hari ini engkau harus bertempur. Tak bisa lagi menunda.”
Arjuna menggertakkan gigi. “Aku tak bisa. Beliau… beliau kakekku.”
Namun medan perang tidak mengenal hubungan darah. Ketika Resi Bisma mulai melangkah maju dan panah-panah dari pihak Kurawa melesat, Arjuna masih terpaku.
Kresna, yang melihat kebekuan Arjuna, akhirnya naik ke kereta, meraih Cakra Beskara yang bersinar menyilaukan. Dengan langkah penuh wibawa, ia berjalan lurus ke depan, arah Resi Bisma.
“Menyingkirlah, Partha! Jika kau tak sanggup menjalankan dharmamu, aku sendiri yang akan mengakhiri ini!” serunya lantang.
Arjuna tersentak. Ia melompat turun dan berlari mengejar Kresna. “Tunggu, jangan! Aku mohon, jangan ikut campur. Biarkan aku yang menghadapinya.”
Kresna berbalik. Matanya menyala dengan kilau kemarahan yang ditahan. “Kau ksatria, Arjuna. Dharma-mu adalah bertarung, bukan menangisi masa lalu. Kau pikir perang ini untuk mainan anak-anak? Jika kau tak sanggup, maka semuanya akan musnah—kau, saudaramu, dan bangsa ini.”
Arjuna terdiam. Lalu ia menunduk dalam-dalam. “Baik, Kresna. Aku akan bertempur.”
Dan ketika genderang perang ditabuh, Arjuna naik kembali ke keretanya. Dengan tangan yang tegas ia mengangkat Gandiva. Anak panah pertama melesat, membelah angin. Resi Bisma menyambut dengan sorot mata yang tak kalah tenang.
Mereka bertarung sepenuhnya. Tak ada kata-kata. Hanya desing panah, tabrakan busur, dan nyala cahaya yang seolah memisahkan siang dan malam. Seolah waktu berhenti untuk menyaksikan pertemuan dua jiwa yang saling menyayangi, namun dipisah oleh takdir.
Arjuna menyerang dengan kecepatan petir, Resi Bisma membalas dengan ketenangan samudra. Tak ada yang saling menahan. Kedua ksatria agung itu tahu: jika rasa ragu ditahan, nyawa lain akan melayang sia-sia. Maka keduanya menumpahkan segalanya dalam anak panah—dharma, cinta, dan perpisahan.
Dari kejauhan, di balik tenda pasukan Kurawa, Adipati Karna mengamati pertarungan itu dalam diam. Matanya menyipit. Bibirnya menegang.
“Inilah sebabnya aku menolak dia jadi senopati,” desisnya pelan. “Resi Bisma tak akan pernah sepenuhnya berpihak pada kami. Hatinya terlalu condong pada Pandawa.”
Ia menoleh pada tombaknya sendiri, menggenggamnya, lalu melepaskan lagi dengan getir. Dilarang ikut berperang oleh Resi Bisma adalah penghinaan yang belum selesai. Ia marah—pada Resi Bisma, pada Kurawa, pada takdir. Tapi hari itu, ia hanya bisa menjadi bayang-bayang, menyaksikan pertarungan yang bukan miliknya.
Ketika matahari mulai condong ke barat dan pasukan dari kedua belah pihak mundur sementara, medan perang menjadi sunyi kembali. Tubuh-tubuh terbaring, darah mengering di tanah. Arjuna berdiri sendiri di tepi perkemahan Pandawa. Matanya kosong, tapi hatinya penuh gejolak.
Kresna mendekatinya perlahan.
“Sudah selesai untuk hari ini,” ucapnya.
Arjuna tak menjawab. Hanya menatap langit yang mulai merah saga.
“Aku benci ini semua,” katanya akhirnya. “Aku tidak ingin menyakiti beliau. Tapi aku tahu, aku harus.”
Kresna duduk di sampingnya. “Perang tidak membedakan kasih dan benci. Dharmamu adalah menegakkan kebenaran. Dan kadang, kebenaran harus ditegakkan di atas hati yang patah.”
Sunyi.
Arjuna mengangguk pelan. Tak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Tapi malam akan datang, dan esok hari, pertempuran akan kembali. Maka untuk malam ini, mereka duduk berdua, tanpa busur, tanpa panah, hanya dua jiwa yang lelah—dalam perang, dalam cinta, dalam dharma.
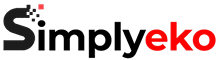
Leave a Reply