
Fajar menyingsing di Kurukshetra dalam semburat merah darah. Angin yang berembus membawa bau hangus, bukan dari api, tapi seolah dari tulang dan daging yang terbakar. Burung-burung hitam berputar membentuk lingkaran di langit, lalu menghilang ke balik awan. Tanda-tanda itu tak terabaikan. Hari ini, Kurawa membentang Cakrawyuha, formasi lingkaran maut, sementara Pandawa menyiapkan Bajrawyuha, tajam dan memecah segala pertahanan. Tapi udara terlalu berat. Bahkan bumi pun seperti menahan napasnya.
Di tengah medan, Prabu Matswapati dari Wirata berdiri di atas keretanya, baju zirahnya bersinar keemasan dalam sinar pagi. “Hari ini kita bukan hanya bertempur,” katanya pada pengiringnya. “Kita membayar janji pada negeri.”
Tanpa ragu, ia melesat menerobos formasi Kurawa. Panah dan tombak mengarah padanya, namun Matswapati menangkis semuanya. Ia menyerang seperti kilat, memimpin pasukannya dengan pekik yang menggema. Tapi di tengah lintasan cakrawyuha, ia berhadapan dengan Resi Durna.
“Undurlah, Matswapati,” ucap sang resi. “Jiwamu terlalu terang untuk dipadamkan hari ini.”
“Jika terang itu hanya bersinar dalam ketakutan, biar padam sekalian!” balas sang raja.
Duel mereka mengguncang bumi. Senjata beradu, mantra dilepaskan, kuda mengamuk. Tapi Durna adalah gunung tua yang belum runtuh. Dengan satu panah sakti, ia menembus dada Matswapati. Sang raja tidak menghindar. Ia menerima panah itu dengan dada terbuka. Tubuhnya roboh perlahan dari atas kereta, suaranya terdengar menggema: “Wirata… hormatku padamu…”
Dan bendera negeri itu jatuh bersamaan dengannya—lambat, gagah, dan tragis.
Di sisi lain medan, empat pertarungan hebat berkecamuk. Gatotkaca bertempur di langit melawan Prabu Bogadenta. Abimanyu bertempur garang menghadapi Prabu Salya. Arjuna kembali menantang Resi Bisma. Tapi sorotan langit seakan berpusat pada satu titik: Dewi Srikandi melawan Bambang Aswatama.
Aswatama menyeringai saat melihat lawannya. “Kau pikir perempuan bisa menembus pelindung para ksatria?”
Srikandi tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu melepaskan panahnya. Duel pun meledak.
Aswatama menyerang cepat, mengandalkan mantra dan kekuatan warisan ayahnya. Tapi Srikandi bertahan kokoh. Setiap panah yang ia lepaskan membawa kehendak: bahwa perempuan bukan bunga, melainkan petir yang bisa menyambar harga diri para laki-laki congkak. Dalam hitungan waktu, keangkuhan Aswatama mulai goyah. Ia berdarah, bukan hanya di tubuh, tapi di keyakinannya. Dan seluruh medan melihat: kemenangan Srikandi hari itu bukan soal kekuatan, tapi kehormatan.
Sementara itu, Arya Drestajumena menemukan Prabu Duryudana di tengah medan dan mengejarnya tanpa ampun. Mereka bertarung garang, tapi semangat Drestajumena menggelegak seperti magma yang lama terpendam. Ia menebas bahu Duryudana, membuat sang raja berlutut dan megap-megap. Saat pedangnya terangkat untuk menyelesaikan segalanya, tiba-tiba sesosok licik muncul dari balik kabut—Arya Sangkuni.
Sebuah senjata kecil berbalut racun menghantam lengan Drestajumena, cukup untuk membuatnya terganggu sepersekian detik. Dan dalam detik itulah Sangkuni menyeret keponakannya kabur ke belakang garis Kurawa.
“Lain waktu kau akan kuhabisi tanpa gangguan, Duryudana!” teriak Drestajumena, penuh amarah dan luka di hatinya.
Sore semakin merambat. Cahaya emas mulai membasuh Kurukshetra. Di tengah kabut debu dan darah, Dewi Srikandi melangkah ke depan garis pasukan. Ia menatap tajam ke arah seorang tua berjubah putih yang berdiri angkuh di antara pasukan Kurawa.
“Resi Bisma,” katanya pelan namun jelas, “hari ini adalah hari kami.”
Tapi Bisma tidak menjawab. Ia memandang ke arahnya, namun wajah Srikandi perlahan berubah di mata sang resi. Bukan seorang wanita muda yang ia lihat—melainkan Dewi Amba, wanita yang dulu mencintainya, dan mati oleh sumpah dan tindakannya sendiri. Bisma menahan napas.
Tangannya bergetar.
Ia berbalik, tidak menyerang. Langkah kakinya membelok ke arah pasukan Pandawa, yang segera dihantamnya seperti badai tua yang belum usai.
Srikandi tak mengejar. Ia tahu, luka yang ia torehkan hari ini belum berdarah, tapi telah menembus lebih dalam dari senjata mana pun.
Matahari akhirnya tenggelam di barat. Genderang perang dihentikan. Sangkakala ditabuh tiga kali. Pasukan ditarik. Tubuh-tubuh dikumpulkan. Tangisan ditahan. Teriakan tercekik.
Dan di Hastinapura yang jauh dari medan, seorang ayah duduk terpaku di singgasananya.
“Anak-anakku…” bisik Prabu Drestarata, buta namun mendengar semua kekalahan itu dari kata demi kata. “Mengapa mereka gugur satu per satu?”
Arya Sanjaya berdiri di sampingnya, wajahnya tenang namun hatinya seperti karang yang menahan badai.
“Paduka,” katanya lembut. “Jangan tangisi buah dari pohon yang sendiri ditanam. Mereka tidak dibimbing oleh kebenaran, tapi oleh angkara.”
Drestarata menangis, tangannya mencengkeram tongkat seolah ingin meremukkan penyesalan yang sudah tak bisa kembali.
Sanjaya meletakkan tangan di dadanya, lalu menambahkan, “Namun jangan bersedih, Prabu. Mereka gugur di medan dharma. Jiwa mereka dibawa ke surga sebagai ksatria. Mereka tidak hilang—hanya dipanggil lebih dulu.”
Tak ada kata lagi setelah itu.
Malam pun turun perlahan, menyelimuti Kurukshetra dengan kabut, luka, dan nyanyian diam dari para arwah yang tak ingin dilupakan.
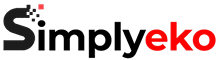
Leave a Reply